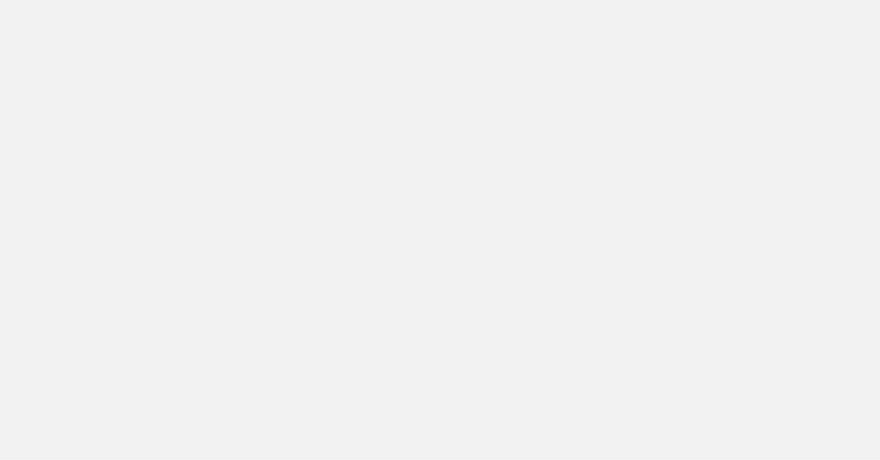Doa Setelah Pulang Haji: Ucapan Syukur dan Harapan untuk Tetap Istiqamah
Stylesphere – Menunaikan ibadah haji merupakan impian mulia bagi setiap Muslim. Setelah melewati serangkaian ibadah yang sarat dengan pengorbanan, keikhlasan, dan kesabaran di Tanah Suci, momen kepulangan jemaah haji ke tanah air menjadi saat yang sangat dinanti dan penuh haru.
Di tengah kegembiraan keluarga dan kerabat yang menyambut dengan suka cita, momen ini sebaiknya juga disertai dengan doa-doa penuh makna. Doa kepulangan dari haji tidak hanya menjadi ungkapan rasa syukur atas keselamatan dan kelancaran perjalanan, tetapi juga merupakan ikhtiar spiritual untuk menjaga kemabruran haji yang telah diperjuangkan.
Dengan doa, seorang haji memohon kepada Allah agar diberikan keistiqamahan dalam beribadah, serta memohon keberkahan bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakat sekitarnya. Doa ini menjadi langkah awal dalam mempertahankan semangat ibadah dan nilai-nilai yang didapat selama berada di Tanah Suci.
Dalam panduan ini, terdapat beberapa doa yang dianjurkan dibaca usai pulang dari ibadah haji, baik untuk diri sendiri maupun oleh para penyambut sebagai bentuk penghormatan dan harapan atas haji yang mabrur.
Berikut adalah rangkaian doa-doa yang dapat diamalkan, sebagaimana dikutip dari laman Anugerahslot Online Lampung, Senin (9/6/2025).
Rangkaian Doa Setelah Pulang Haji: Ucapan Syukur dan Permohonan Keberkahan

Menunaikan ibadah haji adalah puncak spiritualitas bagi seorang Muslim, yang sarat dengan pengorbanan, keikhlasan, dan penguatan iman. Setelah menjalani seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci, kepulangan para jemaah haji ke kampung halaman menjadi momen istimewa yang tak hanya disambut dengan suka cita keluarga, tetapi juga diiringi dengan doa-doa penuh makna.
Doa ketika pulang dari haji bukan sekadar ungkapan syukur atas perjalanan yang selamat, tetapi juga menjadi ikhtiar untuk menjaga kemabruran haji dan memohon agar semangat ibadah terus terjaga dalam kehidupan sehari-hari.
Berikut ini adalah beberapa doa yang dianjurkan dibaca saat pulang dari haji, baik oleh jemaah haji sendiri maupun oleh keluarga yang menyambut:
1. Doa Ketika Telah Sampai di Tanah Air
آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ، سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ
Âyibûna, tâ’ibûn, ‘âbidûn, sâjidûn li rabbinâ hâmidûn.
Artinya:
(Kami) pulang, bertobat, menyembah, bersujud, dan memuji Tuhan kami.
Doa ini dibaca sebagai bentuk syukur atas kembalinya jemaah ke tanah air dengan selamat serta sebagai pengakuan atas ibadah yang telah dijalani dengan penuh keikhlasan.
2. Doa Saat Memasuki Kampung Halaman
بسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إنِّي أسألُكَ خَيْرَها وَخَيْرَ أهلها وَخَيْرَ ما فِيها، وأعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّها وَشَرّ أهلها وَشَرّ مَا فِيهَا
Bismillâh, allâhumma innî as-aluka khairahâ wa khaira ahlihâ wa khaira mâ fîhâ, wa a‘ûdzubika min syarrihâ wa syarri ahlihâ wa syarri mâ fîhâ.
Artinya:
Dengan nama Allah, ya Allah, aku memohon kepada-Mu kebaikan kampung ini, kebaikan penduduknya, dan kebaikan apa yang ada di dalamnya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukan kampung ini, keburukan penduduknya, dan keburukan apa yang ada di dalamnya.
Doa ini mencerminkan harapan agar kepulangan membawa kebaikan, serta perlindungan dari potensi keburukan di tempat yang dituju.
Dengan membaca doa-doa ini, diharapkan para jemaah haji tidak hanya kembali secara fisik, tetapi juga membawa pulang ruh spiritual haji ke dalam kehidupan mereka. Doa menjadi jembatan antara ibadah yang telah dijalani dan komitmen untuk terus memperbaiki diri serta memberi manfaat bagi lingkungan sekitar
Semoga haji yang telah dilaksanakan diterima Allah sebagai haji yang mabrur, dan menjadi titik awal kehidupan yang lebih berkah dan bermakna.
Doa-Doa Kepulangan dari Ibadah Haji: Menyambut dengan Syukur dan Harapan

Kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci adalah momen penuh haru dan kebahagiaan, tidak hanya bagi para jemaah itu sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat yang menanti. Di tengah suka cita, alangkah baiknya momen ini disertai dengan doa-doa syukur dan harapan, sebagai bentuk penghormatan terhadap ibadah yang telah dijalani, serta untuk menjaga semangat dan kemabruran haji yang diraih.
Berikut adalah rangkaian doa-doa yang dianjurkan untuk dibaca oleh jemaah maupun orang-orang yang menyambut mereka:
1. Doa Syukur Saat Kembali ke Tanah Air
آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ، سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ
Âyibûna, tâ’ibûn, ‘âbidûn, sâjidûn li rabbinâ hâmidûn.
Artinya:
(Kami) pulang, bertobat, menyembah, bersujud, dan memuji Tuhan kami.
2. Doa Memasuki Kampung Halaman
بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا
Bismillâh, allâhumma innî as-aluka khairahâ wa khaira ahlihâ wa khaira mâ fîhâ, wa a‘ûdzubika min syarrihâ wa syarri ahlihâ wa syarri mâ fîhâ.
Artinya:
Dengan nama Allah, ya Allah, aku memohon kepada-Mu kebaikan kampung ini, kebaikan penduduknya, dan kebaikan apa yang ada di dalamnya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukan kampung ini, keburukan penduduknya, dan keburukan apa yang ada di dalamnya.
3. Doa Pertobatan yang Mendalam
تَوْبًا تَوْبًا، لِرَبِّنَا أَوْبًا، لَا يُغَادِرُ حُوْبًا
Tauban, tauban, li rabbinâ awban, lâ yughâdiru hûban.
Artinya:
Kami sungguh memohon pertobatan. Kepada Tuhan kami, kami kembali, tobat yang tidak menyisakan dosa.
4. Doa dari Keluarga dan Penyambut Jemaah
قَبَّلَ اللهُ حَجَّكَ، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ، وَأَخْلَفَ نَفَقَتَكَ
Qabballallâhu hajjaka, wa ghafara dzanbaka, wa akhlafa nafaqataka.
Artinya:
Semoga Allah menerima ibadah hajimu, mengampuni dosamu, dan mengganti pengeluaranmu.
5. Doa dari Riwayat Imam Al-Baihaqi
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْحَاجِّ وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الحَاجُّ
Allâhummaghfir lil hâjj, wa li man istaghfara lahul hâjj.
Artinya:
Ya Allah, ampunilah dosa jemaah haji ini dan dosa orang yang dimintakan ampun oleh jemaah haji ini.
Membaca dan mengamalkan doa-doa ini saat menyambut kepulangan dari haji merupakan bentuk penghormatan terhadap perjalanan spiritual yang luar biasa. Semoga doa-doa ini menjadi peneguh bagi jemaah agar senantiasa istiqamah dalam kebaikan, serta menjadi sumber keberkahan bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya.