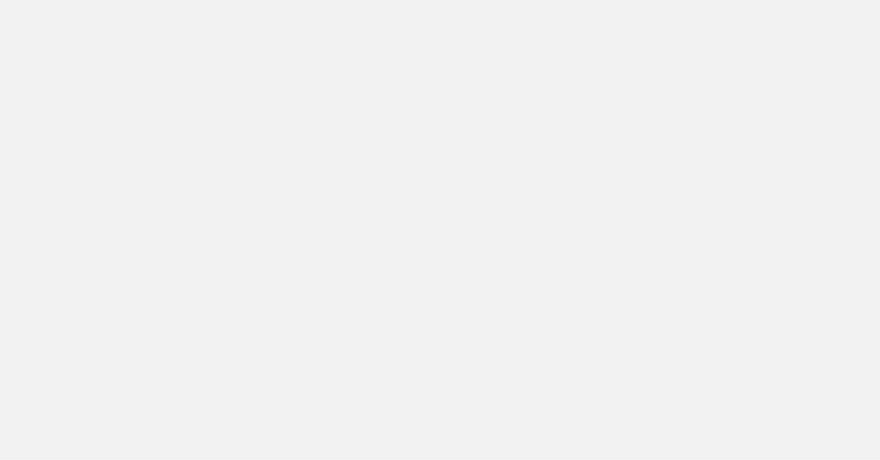Penulisan “Iduladha” yang Benar: Antara Bahasa, Makna, dan Keteladanan
Stylesphere – Setiap tahun, umat Islam di seluruh dunia merayakan dua momen agung yang sarat makna, yaitu Idulfitri dan Iduladha. Kedua hari raya ini bukan sekadar tradisi keagamaan, melainkan juga momentum spiritual dan sosial yang mendalam. Iduladha, secara khusus, menjadi pengingat akan nilai pengorbanan, ketaatan, dan keikhlasan, seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim AS dan putranya, Nabi Ismail AS.
Namun, di tengah gegap gempita perayaannya, terdapat satu aspek yang sering terabaikan: penulisan istilah “Iduladha” yang benar dalam bahasa Indonesia. Tak jarang kita menjumpai variasi penulisan seperti “Idul Adha”, bahkan di media massa dan dokumen resmi. Pertanyaannya: mana yang tepat secara kaidah bahasa?
Penulisan yang Benar: “Iduladha”
Berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) dan referensi dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), penulisan yang benar dan baku adalah Iduladha, ditulis serangkai tanpa spasi.
Hal ini serupa dengan penulisan istilah lain seperti:
- Idulfitri (bukan Idul Fitri)
- Ramadhan (bukan Ramadan, jika mengikuti transliterasi Indonesia)
Kata “Iduladha” berasal dari bahasa Arab ‘Īd al-Aḍḥā (عيد الأضحى), yang secara harfiah berarti “Hari Raya Kurban”. Dalam proses penyerapan ke bahasa Indonesia, unsur fonetik disesuaikan, dan kata depan (Idul) digabungkan dengan kata berikutnya (adha) untuk membentuk satu kesatuan istilah.
Mengapa Ini Penting?
Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, memahami penulisan istilah religius seperti ini bukan sekadar soal teknis. Ini juga merupakan bentuk kepedulian terhadap pelestarian bahasa nasional, serta menghormati makna sakral dari istilah tersebut.
Ketika kita menulis dengan benar, kita:
- Menunjukkan kesadaran literasi bahasa
- Menghargai struktur dan sejarah bahasa serapan
- Memberikan contoh baik dalam komunikasi publik, terutama di ruang media dan pendidikan
Kesimpulan: Bahasa adalah Cerminan Keteladanan
Iduladha mengajarkan kita arti ketaatan yang murni dan pengorbanan yang tulus. Dalam konteks bahasa, ketaatan bisa dimaknai sebagai kedisiplinan dalam berbahasa, termasuk dalam menulis istilah keagamaan dengan benar. Mulai dari hal kecil seperti penulisan “Iduladha”, kita turut menjaga integritas bahasa sebagai sarana dakwah, komunikasi, dan peradaban.
Iduladha atau Idul Adha? Ini Penulisan yang Benar Menurut KBBI
Dalam praktik sehari-hari, penulisan istilah hari raya umat Islam ini memang kerap bervariasi. Sebagian orang menulis “Idul Adha” dengan spasi, sementara lainnya memilih bentuk “Iduladha” tanpa spasi. Lalu, yang manakah yang benar secara kaidah bahasa Indonesia?
Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi VI yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, penulisan yang baku dan benar adalah “Iduladha”, ditulis dalam satu kata tanpa spasi.
Jika Anda mencoba mencari entri “Idul Adha” secara terpisah di situs resmi KBBI, tidak akan ditemukan hasil pencarian. Sebaliknya, ketika mengetik “Iduladha”, akan muncul definisi resmi sebagai berikut:
Iduladha (n): hari raya haji yang jatuh pada tanggal 10–13 Zulhijah, disertai dengan penyembelihan hewan kurban (seperti sapi, kambing, atau unta) bagi yang mampu.
Dengan demikian, “Idul Adha” dikategorikan sebagai bentuk tidak baku, meskipun masih umum ditemukan dalam media, percakapan, maupun tulisan informal.
Hal serupa juga berlaku untuk istilah “Idulfitri”, yang sering salah ditulis menjadi “Idul Fitri”. Menurut kaidah bahasa Indonesia, kedua istilah tersebut merupakan bentuk serapan utuh dari bahasa Arab yang seharusnya ditulis serangkai.
Kesimpulan
Sebagai pengguna bahasa Indonesia yang baik, penting bagi kita untuk membiasakan penulisan yang benar sesuai dengan standar baku. Menggunakan bentuk seperti “Iduladha” dan “Idulfitri” bukan hanya mencerminkan ketepatan berbahasa, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap kaidah kebahasaan yang benar dan berwibawa.
Asal Usul dan Makna Kata “Iduladha”

Secara etimologis, istilah Iduladha berasal dari bahasa Arab ‘Īd al-Aḍḥā.
- Kata ‘Īd (عيد) berarti “hari raya” atau “perayaan”.
- Sementara Aḍḥā (الأضحى) berasal dari kata aḍḥiyah (أضحية), yang berarti “kurban” atau “hewan sembelihan”.
Gabungan kedua kata ini, ‘Īd al-Aḍḥā, secara harfiah bermakna “hari raya kurban” atau “hari raya penyembelihan”.
Dalam sejarah Islam, Iduladha memperingati momen luar biasa ketika Nabi Ibrahim a.s. menunjukkan ketundukannya kepada perintah Allah SWT untuk mengorbankan putranya, Nabi Ismail a.s. Sebuah peristiwa yang menggambarkan ketaatan, keikhlasan, dan pengorbanan total dalam menjalankan kehendak Ilahi.
Istilah Lokal di Indonesia
Di tengah masyarakat Indonesia, Iduladha juga dikenal dengan beberapa nama lain yang mencerminkan kekayaan budaya lokal, antara lain:
- Lebaran Haji – karena bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
- Lebaran Besar – merujuk pada perayaannya yang dianggap lebih megah dibandingkan Idulfitri.
- Hari Raya Kurban atau Idul Kurban – menekankan pada tradisi penyembelihan hewan kurban.
Meski istilah-istilah lokal ini cukup populer dalam penggunaan sehari-hari, hanya bentuk “Iduladha” yang diakui secara baku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).