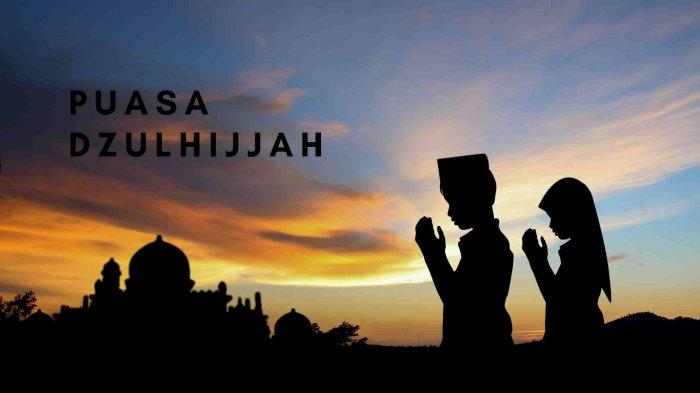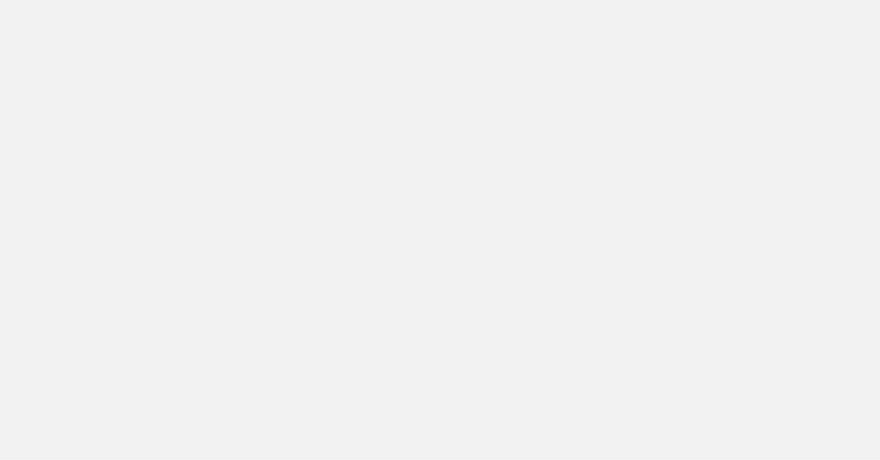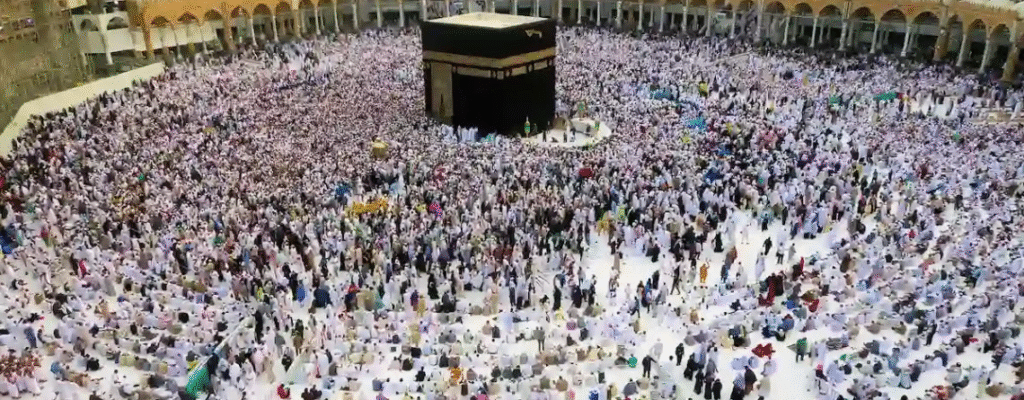Kisah Sebuah Amalan Kecil yang Membawa Berkah bagi 600 Ribu Jemaah Haji
Stylesphere – Di antara jutaan langkah yang menapak di Tanah Suci, tersimpan beragam kisah menakjubkan yang lahir dari kerendahan hati dan ketulusan para jemaah dalam menjalankan ibadah haji. Di tengah kerumunan manusia yang datang dari penjuru dunia, tak jarang muncul cerita sederhana yang menyimpan hikmah luar biasa—bukan hanya bagi pelakunya, tetapi juga bagi ratusan ribu jiwa lainnya.
Amalan kecil yang dilakukan dengan niat tulus dan hati penuh keyakinan, nyatanya dapat menjadi sebab turunnya keberkahan yang meluas. Seolah alam pun menjadi saksi bahwa tidak ada amal baik yang sia-sia di hadapan Allah. Bahkan, balasannya tak hanya kembali kepada si pelaku, tetapi juga menyebar membawa kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya.
Salah satu kisah penuh makna tersebut datang dari Tanah Suci, tentang seorang hamba dengan amalannya yang sederhana namun ikhlas. Kisah ini menjadi sebab diterimanya haji sebanyak 600 ribu jemaah. Sebuah peristiwa yang menggambarkan betapa luar biasanya dampak dari amal yang dilakukan dengan hati bersih, tanpa pamrih.
Kisah ini dirangkum dari laman Anugerahslot Online, dan dipublikasikan pada Sabtu (14/6/2025). Ia menjadi pengingat bahwa keikhlasan sejati dalam beramal mampu mengundang rahmat Allah yang begitu luas, bahkan hingga mabrurnya haji ratusan ribu orang.
Tak Jadi Berhaji, Tapi Jadi Sebab Mabrurnya 600 Ribu Jemaah

Kisah mengharukan datang dari seorang tukang sol sepatu bernama Ibnu Muwafaq, yang menjadi teladan dalam keikhlasan dan kedermawanan. Setelah ditelusuri lebih dalam, diketahui bahwa ia sebenarnya tidak berangkat haji. Keputusan itu diambil bukan karena alasan fisik atau teknis, melainkan karena pilihan mulia: ia menyedekahkan seluruh biaya haji yang telah ia kumpulkan selama 30 tahun untuk membantu sebuah kampung miskin.
“Padahal, Ibnu Muwafaq mengumpulkan biaya hajinya selama tiga dekade dengan bekerja keras sebagai tukang sol sepatu. Namun, demi membantu orang-orang yang lebih membutuhkan, ia relakan niat hajinya,” tutur Kiai Taufik saat mengisahkan peristiwa ini.
Apa yang terjadi setelahnya sungguh luar biasa. Berkat ketulusan dan pengorbanan Ibnu Muwafaq, Allah menerima ibadah haji seluruh jemaah yang berhaji pada tahun itu. Kisah ini menjadi bukti bahwa keikhlasan dan amal sosial bisa menjadi sebab turunnya rahmat yang meluas.
Dalam riwayat lain yang disampaikan oleh Kiai Taufik, disebutkan bahwa pada waktu itu hanya ada enam orang yang benar-benar memperoleh gelar haji mabrur. Namun, masing-masing dari enam orang ini membawa keberkahan yang luar biasa—kemabruran mereka menjadi sebab diterimanya haji dari 600 ribu orang. Artinya, satu orang menularkan kemabruran kepada 100 ribu jemaah lainnya.
“Jadi, ternyata ada ibadah yang nilainya di sisi Allah bisa melebihi haji, yakni kedermawanan, empati, dan kasih sayang terhadap sesama, terutama kepada orang-orang yang lemah,” ungkap Kiai Taufik.
Kisah ini menjadi pelajaran berharga bahwa amal yang dilakukan dengan penuh cinta dan keikhlasan, sekecil apa pun bentuknya, dapat membawa dampak besar. Bahkan, bisa lebih utama dari ibadah fisik apabila dilandasi kasih sayang dan kepedulian sosial yang mendalam.
Tak Ikut Berhaji, Tapi Hajinya yang Diterima: Kisah Ibnu Muwafaq dan 600 Ribu Jamaah
Dalam sebuah kesempatan, Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta, KH Taufik Damas, membagikan sebuah kisah inspiratif yang sarat makna. Ia menceritakan tentang satu orang yang hajinya dinyatakan mabrur di antara 600 ribu jemaah lainnya—meskipun orang tersebut justru tidak berangkat ke Tanah Suci.
Kisah ini, menurut Kiai Taufik, berasal dari khazanah tasawuf dan berawal dari mimpi Ibnu Mubarak, seorang ulama besar, saat menjalankan ibadah haji. Dalam mimpinya, Ibnu Mubarak menyaksikan dua malaikat yang sedang berdialog, membahas siapa di antara ratusan ribu jemaah haji yang hajinya diterima oleh Allah pada tahun itu.
“Dalam mimpi itu, ternyata hanya satu orang yang mendapatkan haji mabrur,” tutur Kiai Taufik melalui akun Twitter pribadinya, Sabtu (5/6/2021). “Yang mengejutkan, orang itu tidak ikut berhaji. Namanya Ibnu Muwafaq.”
Ternyata, lanjutnya, Ibnu Muwafaq telah mengumpulkan biaya haji selama 30 tahun dari hasil pekerjaannya sebagai tukang sol sepatu. Namun, ketika kesempatan berhaji akhirnya tiba, ia memilih untuk menggunakan dana itu untuk membantu sebuah kampung miskin yang sangat membutuhkan.
Keputusannya untuk mendahulukan kebutuhan orang lain dibanding ibadah pribadi yang agung, menjadi bukti keikhlasan dan empati yang luar biasa. Karena niat dan pengorbanan yang tulus itu, Allah memberinya balasan yang tak terbayangkan—hajinya diterima, bahkan tanpa ia menjejakkan kaki di Tanah Suci.
Kisah ini menjadi pengingat kuat bahwa ibadah sejati tidak hanya soal rukun-rukun lahiriah, tapi juga soal hati, niat, dan pengorbanan. Dalam pandangan spiritual, kedermawanan dan kasih sayang kepada sesama bisa memiliki nilai ibadah yang luar biasa tinggi di sisi Allah.